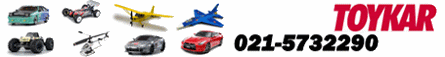Bagi sebagian kalangan, hasil survei itu tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, Jokowi baru empat bulan terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Masyarakat masih memberi kesempatan sembari menunggu penunaian janji-janji. Lebih dari itu, gaya kepemimpinan Jokowi yang mengandalkan “blusukan” dinilai mampu menjaga optimisme publik. Bahkan pada tataran tertentu, gaya tersebut melahirkan kesan politik tersendiri sebagai pemimpin yang merakyat.
Menjaga optimisme jadi faktor penting di tengah semakin pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Sejumlah calon presiden daur ulang tidak begitu laku meski tingkat popularitasnya cukup tinggi. Masyarakat condong mencari figur baru yang lebih menjanjikan ketimbang figur lama. Sekuat apapun pencitraan diri, integritas personal lebih menentukan elektabilitas seorang calon.
Namun, apakah hasil survei itu sejalan dengan prestasi Jokowi memimpin Jakarta? Benarkah Jokowi betul-betul mampu menjaga harapan publik? Jawaban atas pertanyaan ini sangat terkait dengan waktu dilaksanakannya survei. Setiap survei punya jangka tertentu yang bersifat tentatif. Dan, karena survei dilakukan di saat warga DKI baru saja melewati masa bulan madu kepemimpinan, maka sosok Jokowi relatif diuntungkan.
Jika mau jujur, kepemimpinan Jokowi masih seumur jagung. Menilai kiprahnya dalam rentang itu terlalu prematur. Begitu banyak persoalan yang harus diurai sebelum masuk ke tahap kesimpulan. Pelbagai tantangan yang mendera Ibu Kota perlu dijawab dengan program nyata dan berkesinambungan. Masalah banjir, kemacetan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kampung kumuh, dan anak jalanan (kesejahteraan sosial) merupakan sederet masalah yang mesti segera diselesaikan.
Langkah Jokowi
Seiring perjalanan waktu, integritas Jokowi akan terus diuji. Masyarakat senantiasa menunggu terobosan apa yang akan dilakukan. Meski langkah-langkah awal sudah mulai terbaca, nampaknya hal itu masih jauh dari kata ‘memuaskan’. Semua yang dihadirkan hanya sebatas menahan harapan yang hampir karam. Kebijakan Jamkesda dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) misalnya, belum memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat.
Pemasaran kebijakan itu memang berhasil menjaga harapan masyarakat terutama rakyat miskin (wong cilik). Tetapi karena tidak diikuti oleh kerangka programatik yang mengedepankan penataan struktural pada tataran sistem, maka penerapannya tak berjalan mulus. Rumah sakit dan Puskemas kewalahan, sarana dan prasarana medis kurang memadai, KJS digunakan tak sewajarnya, dan lain-lain. Dalam artian, ada lubang yang menganga antara harapan dan kenyataan.
Terkesan, cara berpikir Jokowi mendekati masalah cenderung “apa adanya” tanpa memperhitungkan banyak sisi. Prinsipnya, yang penting ada dan bisa ditangani secara taktis. Sehingga, wajar bila beberapa hari lalu masyarakat digemparkan dengan kasus Dera Nur Anggraini yang ditolak oleh delapan Rumah Sakit, gagal mendapat penanganan medis dan akhirnya meninggal dunia. Kasus Dera kemudian diikuti Upik yang divonis meninggal dunia dalam keadaan masih bernafas.
Begitu pula dengan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP), program kampung deret, pembangunan MRT dan monorail, pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), kebijakan transportasi massal dan kebijakan lain menyangkut kepentingan umum. Walaupun masih tahap permulaan, langkah Jokowi seperti tak terencana. Kegesitan dan kesigapannya di lapangan belum membuahkan satu konsep perencanaan integral dan berjangka panjang.
Sejatinya, sebagaimana teori kebijakan publik, komplesksitas persoalan di lapangan didekati secara ilmiah untuk merumuskan suatu kerangka kebijakan yang jelas dan terarah. Segenap fakta atau informasi yang didapat dianilisis secara rasional dengan mempertimbangkan dampaknya serta melihat kesiapan intitusi. Dari sini kemudian dapat diambil langkah strategis sebagai implementasi kebijakan. Meski tidak bersifat final, setidaknya masyarakat mengetahui formula dan arah kebijakan sehingga dapat berpartisipasi.
Isu Pinggiran
Sejauh ini, program kebijakan Jokowi lebih banyak menyentuh isu sentral dan seksi sebagaimana disebutkan di atas. Sementara, isu pinggiran (periferial) seperti nasib anak jalanan penataan disiplin pengemudi angkutan umum, dan isu tak seksi lainnya kurang mendapat perhatian.
Terkait anak jalanan, makin hari keberadaannya makin bertambah. Mereka hidup dan beraksi di sepanjang jalan trotoar, lampu merah, angkutan umum, dan di dekat pusat pembelanjaan. Sampai hari ini, malam hari selepas maghrib hingga menjelang larut (sekitar jam 19.00 – 22.00 Wib) di bunderan Hotel Indonesia, bunderan kebanggaan warga ibukota, terlihat anak-anak jalanan/pengamen berkeliaran menunggui Lampu Merah. Kondisi ini jelas memprihatinkan sekaligus membuat resah.
Ada kecenderungan beberapa aksi anak jalanan/pengamen mulai mengarah pada perilaku anarkhis: meminta dengan cara memaksa, mengganggu ketenangan pengendara/penumpang atau pengunjung, bahkan mengancam dengan senjata. Sudah rahasia umum bahwa keberadaan mereka terkungkung oleh kejahatan yang terorganisir (organized crime). Kesehariannya sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun batin tanpa ada perlindungan kemanusiaan.
Kehidupan anak jalanan adalah potret nyata kerasnya kehidupan Ibu Kota. Di samping tertikam oleh keadaan, mereka juga tak punya jaminan kesehatan dan pendidikan. Harapan agar tumbuh sehat dan berkembang cerdas ibarat khayalan belaka. Sejak dini mereka sudah harus berkelahi dengan waktu. Tiap detik hidup mereka dipertaruhkan. Harapan di masa depan, kemerdekaan hidup, akal dan batinnya telah direbut paksa oleh ketidakpastian keadaan.
Bulan lalu, Jokowi memang meresmikan empat panti sosial guna menampung anak jalanan termasuk tuna grahita. Empat panti sosial itu antara lain: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, Panti Sosial Asuhan Anak Putera Utama 2, Panti Sosial Asuhan Anak Utama 6, dan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Namun sayangnya, upaya Jokowi hanya sebatas itu. Belum terlihat konsep matang dan serius dalam rangka menanggulangi anak jalanan.
Apa yang dilakukan Jokowi dengan meresmikan empat panti tersebut tidak jauh beda dengan program KJS. Prinsipnya asal ada. Beberapa panti bahkan sudah dibangun pada masa gubernur sebelumnya. Kegiatan dan pendekatannya pun menyerupai rumah singgah yang dikelola LSM. Hampir tak ada pendekatan baru kecuali mengulang cara lama yang dianggap telah usang.
Padahal seharusnya, paradigma yang dikedepankan ialah bagaimana mengembalikan harapan dan kemerdekaan serta mengembangkan kemampuan akal dan pertumbuhan batin mereka. Tuannya adalah untuk menjadikan manusia yang seutuhnya. Dengan paradigma ini dapat dilakukan diagnosis terhadap masing-masing individu sebagai bahan penyusunan perencanaan lanjutan. Tentu saja semua pihak perlu dilibatkan agar penanganan sesuai harapan.
Sementara mengenai penataan disiplin pengemudi angkutan umum, saya punya pengalaman berharga sebagai pelajaran meski secara fakta sangat memilukan. Ketika melintas di daerah senayan setelah Senayan City, mobil saya ditabrak angkutan kota Koantas Bima karena remnya blong. Kaget bukan kepalang. Tak ada korban, alhmadulillah. Sang sopir diperiksa polisi, ditanyai kelengkapan surat menyurat. Apa lacur, supirnya tidak punya SIM, bisnya tidak ada STNK, bahkan izin KIR-nya sudah kadaluarsa (artinya kendaraan tersebut tidak laik jalan alias membahayakan).
Sungguh fakta yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin kendaraan angkutan ibukota, melintas di jalan megah Asia Afrika, sangat membahayakan warga Jakarta baik sebagai penumpang maupun sesama pengguna jalan. Rem blong, sopir tidak punya SIM, bis tidak ada STNK, dan KIR-nya sudah lewat. Sungguh memilukan sekali (menjurus biadab) potret seperti ini.
Angkutan umum transportasi yang sangat vital di Jakarta, terutama bagi masyarakat kecil, wong cilik. Setiap hari mereka berjubel di bus kota menuju tempat kerja, beraktivitas. Keselamatan mereka sangat bergantung pada kelaikan kendaraan dan si sopir. Mungkin isu ini tidak seksi media, tapi mesti menjadi perhatian serius semua pihak, diprioritaskan, karena berkaitan dengan human security. Dan Jokowi ternyata belum melirik hal krusial ini.
Pertanyaannya, kenapa Jokowi terkesan abai terhadap isu-isu periferal padahal terkait langsung dengan masyarakat kecil? Apakah karena isu itu tidak begitu seksi dan menguntungkan? Apa karena mereka bukan konstituen yang meradang ke Balaikota DKI Jakarta? Dalam perspektif kemanusiaan, semestinya penanganan terhadap hal-hal yang bersentuhan langsung dengan hak hidup dan perlindungan ini diprioritaskan. Sebab, hal ini menyangkut nasib hidup yang senantiasa dipertaruhkan. Tak ada alasan sedikit pun untuk mengesampingkan.
Semoga saja Jokowi tak sekedar menjual harapan wong cilik, waktu akan mengujinya.***