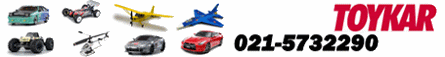Oleh: Fayakhun Andriadi, Anggota Komisi I DPR
Konstruksi kebangsaan Indonesia lahir dari sebuah pergolakan pemikiran panjang yang dilandasi atas kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan dan kebebasan. Kolonialisme yang berlangsung selama lebih tiga abad telah menggugah kognisi bangsa yang pada akhir menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan dan masa depan suatu bangsa hanya bisa diraih dengan sebuah eksistensi kebangsaan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
Gerakan-gerakan kebangsaan yang dimobilisasi oleh kaum terpelajar di bawah panji-panji organisasi kepemudaan, meleburkan sekat-sekat kesukuan dan etnisitas dalam sebuah lingkungan rasional. Sumpah Pemuda yang dikumandang pada 1928 adalah puncak kesadaran kebangsaan yang menegaskan sikap dan karakter sebagai bangsa yang hendak merdeka dan berdaulat.
Kesadaran Kaum Terpelajar
Momentum kesadaran itu pada akhirnya membuahkan hasil dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Keduanya adalah figur pelajar dan terdidik yang berhasil membawa kesadaran kebangsaan ke ranah praktis politik, memperkenalkan Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bersiap menyongsong perubahan dunia di masa yang akan datang.
Perjalanan panjang bangunan keindonesiaan pada akhirnya menegaskan keterlibatan yang cukup besar dari kalangan terdidik kala itu. Hal ini juga membuktikan bahwa kemajuan dan kebesaran sebuah bangsa tidak pernah lepas dari peran pendidikan. Terlepas dari kelahiran kalangan terpelajar dan terdidik tersebut muncul dari kebijakan politik etis kaum kolonial, namun substansi pendidikan sebagai wadah pembentukan karakter dan jati diri kebangsaan tidak bisa dinafikan, hingga pada masa-masa berikutnya mewarnai jatuh-bangunnya sebuah bangsa dalam merespons perkembangan global.
Pendidikan telah menghasilkan perubahan, tidak hanya pada individu terdidik kala itu, tetapi juga memberikan sumbangan pada perubahan sosial-kemasyarakatan. Enyaman pendidikan yang dilalui oleh kalangan muda di era pergolakan kemerdekaan adalah enyaman yang tidak sekedar dilandasi keinginan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran, tapi memiliki tujuan substantif, yakni untuk menciptakan perubahan sosial dan politik. Tentu saja, perubahan tersebut tidak sekedar lahir dari serangkaian kurikulum pendidikan yang justru diproduksi oleh kaum kolonial, namun lahir dari kesadaran kognitif, kesadaran akan latar-belakang historis masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang terjajah.
Pendidikan yang Mengungkung
Asupan pola pendidikan di era pergolakan kemerdekaan itulah yang mencirikan karakter bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Para pendiri bangsa yang merupakan tokoh-tokoh politik berkaliber internasional semisal Mohammad Natsir, Muhammad Yamin, Sutan Syahrir dan lain sebagainya adalah para cerdik pandai yang pernah mengenyam pendidikan formal maupun informal. Namun formalitas pendidikan yang mereka jalani mampu melahirkan nilai-nilai pembebasan bagi masyarakatnya.
Namun hal itu justru cenderung menurun pada masa-masa setelahnya. Memasuki masa-masa di era Orde Baru, pola pendidikan justru sangat diwarnai dengan aroma politisasi yang sangat kental. Kaum terdidik dan terpelajar lahir untuk dirinya sendiri, tidak hadir sebagai agen perubahan (agent of change) yang membawa idealisme kemajuan. Jika pun ada, maka karakter itu hanya muncul secara individual, tidak lahir dari sistem pendidikan yang disepakati dan dijadikan sebagai sistem pendidikan nasional.
Mochtar Buchori mengungkapkan sebuah fenomenon historis terkait dengan pola pendidikan di Indonesia pada periode 1908-1945 dan 1959 dan 1998. Dalam periode 1908-1945 semangat pendidikan adalah “semangat melawan dan membebaskan”. Sementara pada periode 1959-1998, semangat melawan dan membebaskan ini melemah secara sistematis, dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat “mengabdi penguasa”.
Kentalnya aroma politik dalam sistem pendidikan nasional bermuara pada insan-insan terpelajar yang lekang saat berhadapan dengan kebutuhan sosial-kemasyarakatan, dan cenderung buta dalam memandang situasi dan kondisi bangsanya. Hal itulah yang pernah disinyalir oleh pemikir Wina, Ivan Illich, yang mencetuskan gagasan tentang “deschooling society”. Illich menganggap bahwa pendidikan tidak lepas dari kepentingan penguasa, yang pada akhirnya membuat pendidikan tidak bermuara pada pembebasan manusia (dehumanisasi). Karena itu, pendidikan selalu terkait dengan kepentingan politik, termasuk dalam menetapkan kurikulum (Ivan Illich, 1982).
Illich kemudian menyarankan agar pendidikan formal ditolak. Karena melalui pendidikan formal itulah peningkatan ilmu selalu dikaitkan dengan keberhasilan. Imaginasi murid dilatih untuk menerima jasa bukan nilai. Pelembagaan hanya mengakibatkan polusi fisik, polarisasi sosial dan impotensi psikologis. Pada gilirannya, pendidikan lebih tereduksi dalam kaitan kepentingan materi. Pendidikan telah berubah menjadi sarana untuk memperoleh keuntugan ekonomi, digunakan sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan. Pendidikan hanya menjadi sarana, proses pembentukan secara keseluruhan dan bukan untuk tujuan itu sendiri.
Karena itu, tidak sulit menyaksikan betapa kurikulum pendidikan menekankan pada hasil-hasil yang bersifat material. Hingga pada tahap tertentu mengklasifikasi anak didik dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan nilai-nilai yang dihasilkan oleh anak didik. Sekolah menjadi lembaga pendidikan yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang tidak egaliter dan cenderung diskriminatif. Sekolah dianggap sebagai lembaga pendidikan dalam era industri yang telah menjadi sedemikian mekanistik. Penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah merupakan praksis yang tidak sebangun dengan pendidikan itu sendiri. Murid-murid kemudian mempunyai logika baru; belajar dianggap sebagai hasil proses pembelajaran yang diadakan oleh sekolah, semakin banyak pengajaran maka semakin banyak hasilnya, menambah materi maka akan semakin mempermudah keberhasilan.
Anak didik kemudian diberi asupan berbagai macam mata pelajaran yang harus dicerna tanpa analisa, ataupun mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan kepentingan sosial dan kemasyarakatannya. Dalam sistem pendidikan seperti ini, pola pendidikan megandung karakter, seperti yang diistilah diistilahkan oleh Paulo Freire, sebaga “gaya bank”, dengan memosisikan anak didik sebagai objek, bukan subjek pendidikan. (Paulo Freire, 1972). Sebagai objek, dalam proses belajar-mengajar, guru sekedar memindahkan sejumlah dalil dan rumus kepada anak didik, tanpa memberikan pengertian substansial tentang pentingnya dalil dan rumus tersebut.
Pola “gaya bank” inilah yang menempatkan anak didik sebagai pihak yang pasif dan menerima apa saja yang diasupkan kepada mereka. Anak didik diibaratkan sebagai benda mati, yang pasif dan tidak perlu memberikan pilihan-pilihan atas apa yang mereka terima. Hasil dari penerimaan itu akan berkumpul pemikiran anak didik, dan hanya dikeluarkan saat dipertanyakan. Karena itu, hasil dari pendidikan itupun tidak akan berpengaruh signifikan bagi kehidupan sosial, apalagi mengharapkan terjadinya aksi perubahan dari hasil pendidikan.
Alih-alih berharap pada pembebasan dan perubahan, pendidikan justru menghasilkan rasa takut dan cemas. Sangat jelas terlihat, tatkala mendekati masa-masa ujian, anak didik dirundung ketakutan dan kecemasan dengan membayangkan segudang soal-soal yang sulit di hadapan mereka. Kesulitan itu muncul, karena kumpulan soal tersebut harus dijawab dengan mengandalkan kekuatan hafalan, bukan atas dasar analisa yang justru mengundang keberanian anak didik untuk memecahkan persoalan di hadapannya yang tidak harus merujuk pada dalil-dali dan rumus-rumus yang termaktub dalam buku-buku pelajaran.
Pendidikan Nasional
Sistem pendidikan nasional pada dasarnya pernah mengajukan sebuah penerapan pola pendidikan yang membebaskan melalui Cara Belajar Siswa Akit (CBSA). Namun pada kenyataannya, pola tersebut cenderung merupakan slogan, mengingat pola itu hanya metode, tapi dalam penerapannya, materi yang disampaikan merupakan barang asing yang tidak lahir dari konteks dimana manusia itu ada. Pada gilirannya, anak didik kembali menjadi “bank” penyimpan pengetahuan. Memang mahasiswa aktif belajar dan berdiskusi, namun yang dipelajari dan didiskusikan adalah sejumlah dali dan rumus yang tidak ada hubungan dengan kehidupannya. Relasi guru dengan murid pun adalah pengajar dan yang diajar. Murid adalah pihak yang tidak tahu dan harus diberitahu, sedangkan guru adalah pihak yang tahu dan akan memberitahu.
Amanat konstitusional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 cukup memberi garis tegas tentang tujuan, arah dan cita-cita kehidupan bangsa dan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu poin penting dalam tujuan, arah dan cita-cita tersebut terkait dengan peran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itulah yang diimplementasikan dalam UU RI No 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menyebutkan tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Nilai utama yang terkandung dalam tujuan tersebut adalah pembangunan watak dan karakter kebangsaaan (nation character building). Pendidikan harus membantu orang untuk menjadi manusia yang berwatak. Mohammad Hatta membedakan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan membentuk karakater, pengajaran memberikan pengetahuan yang dapat digunakan dengan baik oleh anak-anak yang mempunyai karakter. Maka bagi Hatta yang utama bukanlah sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan, melainkan pendidikan watak yang bisa membuat manusia hidup dalam pergaulan sesama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Watak dan karakter kebangsaan terwujud dengan memaknai pendidikan sebagai usaha bersama dan menempatkan relasi antara peserta didik dengan pendidikan serta sistem yang memicu dan memacu kreatifitas. Kreatifitas itu sendiri akan muncul dengan dukungan sistem pendidikan yang membebaskan. Khususnya dengan mendahulukan kreatifitas dan kecenderungan peserta didikan atas pilihan-pilihan materi tanpa harus semata bergantung pada kurikulum yang justru sangat mungkin berubah-ubah sesuai kecederungan kebijakan politik kekuasaan.
Dengan demikian, tidak ada ruang eksklusif yang seringkali tercipta dalam sistem tersebut, dengan kategorisasi, klasifikasi peserta didik maupun lembaga-lembaga pendidikan, hingga diskriminasi bagi mereka yang mengenyam pendidikan-pendidikan tertentu, karena pendidikan menghasilkan pembebasan dan emansipasi masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan yang menciptakan penderitaan hidup. Karena itu pula, sistem pendidikan tidak akan dipusingkan dengan persoalan-persoalan klasik terkait dengan biaya dan anggaran. Persoalan-persoalan seperti itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga wujud pendidikan tidak lagi bersifat inklusif karena pendidikan menjadi milik semua orang, semua warga negara.
Lebih dari setengah abad, sistem pendidikan terbelenggu oleh kepentingan kekuasaan, menyebabkan pemikiran menjadi sangat sempit. Pendidikan yang seharusnya membebaskan telah dipakai sebagai alat melanggengkan kekuasaan, sehingga hanya membawa sebuah kesenjangan sosial yang semakin lebar antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu. Bagi yang mampu membiayai pendidikannya tentu akan memilih pendidikan yang baik, sehingga nantinya dia juga akan mendapatkan penghasilan yang tinggi karena pendidikannya tersebut. Pendidikan dianggap sebagai sebuah batu loncatan bagi narasi ekonomi yang sudah ada di benak orang tua maupun peserta didik . Pendidikan yang setinggi-tingginya diperoleh hanya untuk mendapatkan gelar bagi pencapaian taraf ekonomi yang lebih baik. Sangat sedikit nilai-nilai yang justru menjadi tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga sangat jarang kita melihat perubahan sosialdihasilkan dari proses pendidikan.
Oleh karena itu, sudah saatnya sistem pendidikan nasional kita merujuk pada tujuan dan cita-cita idealnya sebagai pembentuk watak dan karakter yang pada gilirannya mencirikan peradaban dan martabat bangsa. Pendidikan adalah sarana untuk mencapai tujuan universal kehidupan sebagai manusia yang utuh, tidak parsial. Manusia yang mampu memandang dirinya sebagai subjek sejarah yang mampu menganalisa kehidupan diri dan lingkungannya, atas dasar kemerdekaan, kebebasan dan kedaulatannya.
12 April 2011