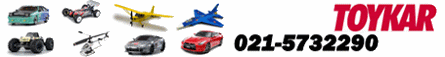Oleh: Fayakhun Andriadi, Anggota Komisi I DPR RI
Persoalan yang kerap menimpa buruh migran Indonesia di luar negeri perlu dilihat secara kritis terkait sikap Pemerintah Indonesia dalam merespons berbagai persoalan TKI. Bagaimana peran institusi-institusi yang harus bertanggung jawab sesuai beban kerjanya dalam menghadapi kasus tersebut? Apa rekomendasi penting yang perlu diambil pemerintah ke depan dalam upaya lebih meningkatkan mutu perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri?
Kasus Ruyati, TKI pembantu rumah tangga (PRT) yang diekseskusi pancung di Arab Saudi baru-baru ini, tidak lebih dari sebuah fenomena gunung es (iceberg phenomenon) yang menimpa para tenaga kerja kita di luar negeri. Kasus-kasus serupa dapat dipastikan masih banyak dialami oleh para pahlawan devisa itu.
Munculnya kembali kasus kekerasan yang menimpa para TKI belakangan ini seperti menunjukkan ketidakmampuan bangsa ini mengambil pelajaran atas pelbagai kasus yang sama terjadi di masa sebelumnya. Untuk menyebut sejumlah kasus yang cukup menyita perhatian publik, di antaranya kasus TKI Nirmala Bonat yang luka parah akibat sering disiksa majikannya pada tahun 2004 dan kasus yang sama juga menimpa Ceriyati, TKI asal Brebes, Jateng, pada 2007. Setahun kemudian, seorang TKI, Siti Hajar, kabur dari apartemen majikannya karena tidak tahan sering disiksa. Hingga kini kekerasan terhadap TKI seperti tak pernah usai.
Di negara tempat penempatan, TKI kita umumnya mengalami kekerasan berupa gaji tidak dibayarkan, klaim asuransi tidak dibayar, pelecehan seksual, meninggal, penipuan, penelantaran, pengusiran oleh majikan, penyiksaan, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, gagal berangkat, putus komunikasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga sakit yang diabaikan dan pemerasan.
Ironisnya, pulang ke Tanah Air, mereka masih harus menghadapi kasus lainnya. Kali ini adalah aksi pemerasan yang berlaku secara sistemik dengan berlindung di balik kedok administrasi dan birokrasi yang dilakukan baik oleh pihak orang per orang ataupun oleh institusi tertentu.
Seringnya TKI kita mengalami kekerasan karena mereka umumnya bekerja di sektor informal atau domestik, baik sebagai PRT, pengasuh anak atau juru masak di restoran. Bekerja di sektor ini penuh risiko (3D: dark, dirty, dangerous) dengan keadaan yang sangat rendah perlindungannya. (Athukorala, 2003). Mereka pun sangat rentan terjerat sindikat pelacuran dan perdagangan manusia (human trafficking). Sementara untuk sektor lainnya, biasanya dipasok warga negara Filipina, Bangladesh, India, dan Vietnam. Dari sini jelas, posisi tawar negara kita sebagai pemasok tenaga kerja sangat rendah.
Pilihan bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar. Akan tetapi, risiko yang ditanggung pun tak kalah besarnya. Mereka sangat rentan mengalami berbagai perlakuan yang tidak diinginkan. Sejak masa perekrutan, mereka sudah mengalami perlakuan kurang mengenakkan karena aksi para calo yang mengiming-imingi berbagai kemewahan kepada para calon TKI hingga membuat mata rantai itu seperti tak ada putusnya. Di lain pihak, pemerintah sendiri tampaknya seperti tersandera oleh jaringan calo yang sudah sangat menggurita sejak perekrutan TKI.
Akhirnya, kasus Ruyati harus dijadikan hikmah dalam pembenahan masalah TKI, baik sejak perekrutan maupun sampai ke negara penempatan TKI. Ini penting demi perbaikan jaminan perlindungan TKI ke depan. Semua pilihan ini tentu akan sangat tergantung pada posisi politik pemerintah. Namun, ke mana pun arahnya atau kebijakannya, yang paling utama dan terutama adalah kepentingan perlindungan bagi para TKI. ***
Sumber: Suara Karya Online, Selasa, 19 Juli 2011