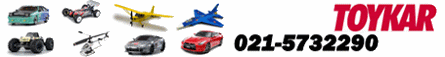BNP2TKI tidak pernah memperlihatkan peran signifikan memberikan perlindungan terhadap TKI. Sekarang hanya ada dua opsi untuk BNP2TKI.
Belum lama kita dibuat sangat bangga sekaligus kagum dengan retorika SBY yang diperlihatkannya di hadapan sidang International Labor Organization (ILO) pada 14 Juni 2011 kemarin. SBY terkesan sangat diplomatis ketika membicarakan mengenai perlindungan PRT migran di Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap PRT migran sudah berjalan, baik itu dengan keberadaan sebuah institusi maupun regulasi.
Dalam kenyataannya, tak selang seminggu pada hari Sabtunya, 18 Juni 2011 muncul pemberitaan yang sangat mengejutkan di sejumlah media internasional. Isinya bagaikan menampar merah muka orang nomor satu di negeri ini, dan tentu saja seluruh rakyat Indonesia. Yakni kasus eksekusi hukuman mati dengan cara dipancung bagi Ruyati binti Sapubi, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia. Kasus ini jelas memperlihatkan fakta yang sangat paradoks dari apa yang dikatakan SBY di forum internasional itu, dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Ironinya lagi, di Indonesia, pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus itu, terkesan lempar tanggung jawab; bahkan saling menuding siapa yang paling berhak mengatasi persoalan itu. Menakertrans menuduh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lalai dengan kasus kematian TKI asal Bekasi itu. Sebaliknya, BNP2TKI menilai pihak kementerian kurang aware dengan para pekerja yang sering disebut sebagai pahlawan devisa negara itu. Sedangkan pihak Kementrian Luar Negeri juga dianggap lalai, tidak mempunyai informasi akurat terkait eksekusi Ruyati.
Persoalan yang kerap menimpa buruh migran Indonesia di luar negeri, perlu dilihat secara kritis : sikap pemerintah kita, dalam merespon berbagai persoalan itu dalam berbagai bentuk kasusnya. Bagaimana peran institusi-institusi yang harus bertanggung jawab sesuai beban kerjanya, dalam menghadapi kasus ini. Apa rekomendasi penting yang harus diambil oleh pemerintah, dalam rangka perbaikan mutu perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Kesedihan yang Tak Pernah Berujung
Kasus Ruyati tidak lebih dari sebuah fenomena gunung es (Iceberg Phenomenon) yang menimpa para tenaga kerja kita di luar negeri. Selain itu, dipastikan lebih banyak dan besar lagi, baik dari segi jumlah maupun kualitas hukumannya yang dialami oleh para pahlawan devisa ini. Menurut Kemenlu sejak tahun 1999 hingga 2011, terdapat 303 warga Indonesia terancam hukuman mati. Dari jumlah itu, tiga di antaranya telah diieksekusi, dua orang dipancung di Arab Saudi dan satu orang di Mesir.
Jumlah ancaman hukuman mati terbesar dialami TKI kita di Malaysia. Yakni sebanyak 233 orang. Kemudian di negara China sebanyak 29 orang, dan diikuti oleh Arab Saudi banyak 28 orang. Sebuah angka yang sangat menggetirkan karena menyangkut nyawa anak bangsa yang berjuang membiayai hidupnya di luar negeri.
Munculnya kembali kasus kekerasan yang menimpa para TKI belakangan ini seperti menunjukkan ketidakmampuan bangsa ini mengambil pelajaran atas pelbagai kasus yang sama terjadi di masa sebelumnya. Untuk menyebut sejumlah kasus yang cukup menyita perhatian publik, di antaranya kasus TKI, Nirmala Bonat yang luka parah akibat sering disiksa majikannya pada tahun 2004 dan kasus yang sama juga menimpa Ceriyati, TKW asal Brebes Jawa Tengah pada 2007. Satu tahun kemudian terjadi lagi, seorang TKI, Siti Hajar kabur dari apartemen majikannya, karena tidak tahan sering disiksa pada tahun 2009. Hingga kini, kekerasan terhadap TKI seperti tak pernah usai.
Menurut data Migrant Care (2011), bila berdasarkan negara penempatan, TKI kita banyak mengalami kekerasan itu di negara yang sering mengklaim sebagai negara serumpun. Yakni Malaysia. Jumlah kekerasan yang menimpa TKI kita di negeri Upin-Ipin ini sebesar 39 persen. Kemudian diikuti oleh Arab Saudi yang sebesar 38 persen. Negara lainnya, seperti Kuwait (5 persen), Hongkong, Taiwan, dan Yordania masing-masing 3 persen, Brunei Darussalam, Singapura, Bahrain, dan Amerika masing-masing 2 persen. Sebuah besaran yang sangat memilukan.
Seringnya TKI kita mengalami kekerasan dikarenakan mereka umumnya bekerja di sektor informal atau domestik, baik sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak atau juru masak di restoran. Sementara untuk sektor lainnya, biasanya dipasok warga negara Filipina, Banglades, India, dan Vietnam. Dari sini jelas, posisi tawar negara kita sebagai pemasok tenaga kerja sangat rendah.
TKI kita yang bekerja di sektor informal adalah jenis pekerjaan yang dibayar lebih rendah untuk kerja yang panjang karena jam kerjanya tidak jelas. Pendapatan mereka di bawah upah minimum sektor jasa di sektor formal seperti di pabrik dan perusahaan. Demikian juga, mereka yang bekerja adalah kaum perempuan.
Dari sisi usia, sebagian besar mereka berada pada usia produktif (di atas 18 tahun sampai 35 tahun), namun ditengarai banyak juga mereka yang sebenarnya berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena mereka banyak yang dipalsukan identitas dokumen perjalanannya. Ruyati yang dapat berangkat ke luar negeri, diduga juga telah melakukan pemalsuan usia.
Pilihan bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar. Akan tetapi, risiko yang ditanggung pun tak kalah besarnya. Mereka sangat rentan mengalami berbagai perlakuan yang tidak diinginkan. Sejak perekrutan mereka sudah mengalaminya. Aksi para calo yang mengiming-imingi berbagai kemewahan kepada para calon TKI itu membuat mata rantai itu seperti tak ada putusnya. Pemerintah seperti tersandera oleh jaringan calo yang sudah sangat menggurita; hampir tak bisa melakukan apa-apa. PJTKI, jelas tidak dapat diabaikan dari konstribusinya terhadap pelanggengan kejahatan itu.
Penderitaan seperti tidak berhenti ketika mereka sudah berada di negara tempat penempatan. Melainkan justru itu menjadi awal bagi penderitaan yang akan mereka alami hingga seterusnya. Karena kebanyakan TKI kita bekerja di sektor informal atau domestik yang penuh risiko (3D: Dark, Dirty, Dangerous) dengan keadaan yang sangat rendah perlindungannya (Athukorala, 2003). Mereka juga sangat rentan terjerak dalam sindikat pelacuran dan perdagangan manusia (human trafficking).
Ruyati adalah gambaran di mana TKI kita mengalami penderitaan yang sangat saat mereka di negara penempatan itu. Buruknya, tidak ada perlindungan dari pemerintah kita. Yang lebih buruk lagi, pemerintah mengaku tidak mengetahui saat pahlawan devisa ini menjalani hukuman pancung. Padahal setiap tahunnya, KBRI Arab Saudi dan KBRI Kuwait mengeluarkan data resmi mengenai jumlah buruh migran yang melarikan diri ke KBRI untuk mencari perlindungan dari tindak kekerasan dan perkosaan majikan mencapai sekitar 3.627 orang. Belum lagi, mereka yang menjadi korban penjualan manusia untuk dijadikan budak pelacuran di negara-negara itu.
Lain di Arab Saudi, lain pula penderitaan TKI kita di negara Malaysia. TKI kita diperlakukan sebagai ”persona non grata”, di mana pemerintahan itu merepresi buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia. Untuk mengusir buruh migran Indonesia tak berdokumen, pemerintah Malaysia tak hanya menerbitkan Akta Imigresen 1154 tahun 2002 tetapi juga melancarkan Ops-Nyah yang mengerahkan tentara dan polisi Malaysia bersenjatakan lengkap. Malaysia pun menggunakan milisi sipil RELA untuk menangkapi buruh migran Indonesia. Mengutip kalimat pak Jusuf Kalla, “di Malaysia ada TKI Ilegal ditangkapi, namun tidak pernah ada Majikan Ilegal yang ditangkap”.
Berbeda dengan yang dialami TKI kita di Hongkong dan Taiwan. Hukum berlaku ketat di negara tersebut, sehingga TKI yang menerima gaji yang lebih rendah, atau mengalami PHK sepihak, kedua belah pihak (majikan dan TKI) diproses berimbang secara hukum.
Dari kasus-kasus itu, bila berdasarkan jenisnya, TKI kita umumnya mengalami kekerasan berupa gaji tidak dibayarkan, klaim asuransi tidak dibayar, pelecehan seksual, meninggal penipuan, penelantaran, pengusiran oleh majikan, penyiksaan, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, gagal berangkat, putus komunikasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, hingga sakit yang diabaikan dan pemerasan.
Jenis-jenis kasus itu merupakan yang dialami TKI kita saat di luar negeri. Pulang ke tanah air, mereka masih harus menghadapi kasus lainnya. Kali ini adalah aksi pemerasan yang berlaku secara sistemik dengan berlindung dibalik kedok administrasi dan birokrasi yang dilakukan baik oleh pihak orang perorang, atau pun oleh institusi seperti oleh sejumlah PJTKI, bahkan ada juga oknum kementerian dan BNP2TKI yang turut bermain dalam air keruh itu. Jadilah para pahlawan devisa itu tak ubahnya seperti sapi perah.
Sungguh memilukan nasib para Pahalwan Devisa tersebut. Tenaga kerja yang menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor Migas ini, hingga kini nasibnya belum juga berubah. Bila dirunut dalam sejarahnya, praktik pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar tahun 1887, di mana banyak TKI yang dikirimkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai buruk kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam, dan Serawak. Saat itu, banyak orang-orang Indonesia yang bekerja dibawah tekanan dan gaji sangat kecil untuk membangun infrastruktur di negara-negara itu. Pada akhir tahun 70-an, terjadi gelombang pengiriman TKI ke negara-negara Timur Tengah secara besar-besaran. Hal itu seiring dengan kebijakan liberalisasi yang diterapkan Orde Baru dan fenomena oil boom yang meningkat di negara-negara itu.
Praktik pengiriman TKI itu bertambah besar volumenya serta jangkauan negara yang menjadi tempat tujuannya. Terlebih gejala itu berubah sangat dramatis ketika terjadi krisis ekonomi nasional pada tahun 1997. Sejak itu, hingga kini gelombangnya hampir tidak pernah surut. Sekalipun banyak yang mengalami penyiksaan dan bahkan pembunuhan, namun tak membuat kapok mereka untuk mengais rezeki di negeri orang. Menurut sumber kementerian, tiga tahun lalu saja, misalnya, jumlah TKI di luar negeri mencapai 696.746, besaran ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya pada 2004 yang mencapai 380.690 orang. Menurut perkiraan Migrant Care (2011), buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri mencapai 4,5 juta orang. Sebagian besar di antara mereka adalah perempuan (sekitar 70 %) dan bekerja di sektor domestik (sebagai PRT) dan manufaktur.
Meski mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tingkat keselamatan dan perlindungan bagi mereka masih menjadi persoalan yang sangat krusial. Fakta yang sangat jelas di hadapan kita, adalah Ruyati itu. Meski jauh sebelum kasus itu muncul, bahwa kasus yang sama juga kerap terjadi dalam setiap tahunnya. Namun keseriusan pemerintah tidak pernah terbukti.
Kesemua penjelasan di atas ini membuktikan sangat jelas kegagalan pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Negara telah melakukan pelanggaran secara sistematis terhadap konstitusi. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab.
Dualisme
Selama ini, ketentuan perlindungan bagi TKI diatur dalam Undang-Undang No 39/2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU itu pula yang mengamanatkan dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (pasal 94 ayat 1 dan 2). Sebuah badan yang bertugas melaksanakan program pelayanan penempatan dan perlindungan TKI G to G dan G to P, berkoordinasi, mengawasi dokumen, pembekalan dan pemberangkatan akhir, penyelesaian masalah, sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, meningkatkan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
BNP2TKI relasinya dengan Kemenakertrans sebagai pelaksana teknis dari kebijakan yang dikeluarkan kementerian dalam penempatan TKI di luar negeri. Dalam kenyataannya, selama ini kedua lembaga ini, karena menyangkut “lahan rezeki”, seringnya berebut peran dalam penempatan TKI. Bahkan keduanya terkesan kuat ada dualisme kepemimpinan dalam menyediakan pelayanan TKI.
Dalam UU No 39 tahun 2004, BNP2TKI melakukan penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan pemerintah G to G dan G to P. Artinya, lembaga ini melayani penempatan TKI yang dilaksanakan pemerintah, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS), TKI mandiri dan penempatan perusahaan sendiri.
Dalam kenyataannya, terbitnya Peraturan Mennakertrans No 22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dan Peraturan Menakertrans No 23 tahun 2008 tentang Asuransi TKI, berdampak pengalihan sejumlah pelayanan administrasi yang selama ini dilakukan oleh BNP2TKI. Sekalipun, kemudian pihak Kementerian mencabut peraturan No 22 tersebut, menggantinya dengan Peraturan Menteri No 15 tahun 2009, namun pihaknya kembali membuat tiga peraturan No 16, 17, dan 18 yang isinya tidak jauh beda dengan peraturan No 22 yang telah dicabut itu.
Dengan adanya peraturan itu, yang selama ini menjadi lahan rezeki BNP2TKI dalam pelayanan administrasi terpaksa harus diambil oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Pelayanan administrasi itu tentu saja sangat “basah” karena meliputi: pembuatan surat izin pengerahan, penyelenggaraan pembekalan akhir penempatan (PAP), pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), sistem komunikasi KTKLN, rekomendasi fiskal, pengawasan lembaga pelatihan, klinik pemeriksaan kesehatan, sertifikasi, asuransi, dan pengelolaan terminal khusus TKI.
Dengan begitu juga, BNP2TKI hanya menempatkan TKI sesuai dengan perjanjian negara asal dan negara tujuan (G to G) yang selama ini terbatas pada penempatan ke Korea Selatan dan Jepang. Sementara negara penempatan lainnya dikelola oleh pemerintah daerah dan sejumlah pihak swasta (PPTKIS) yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah.
Kendati belum lama ini, ikhtiar untuk mengatasi konflik itu berusaha ditempuh oleh Muhaimin dengan terbitnya Peraturan Menteri No 14 tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Penempatan TKI di luar negeri, namun substansinya tetap tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya. Artinya, pihak kemenakertrans masih belum rela memberikan sebagian lahan rezekinya dikelola oleh BNP2TKI.
Bila dilihat dari konteks kemunculan badan organisasi, konflik kepentingan itu sebetulnya tidak lebih dari kelanjutan konflik yang sudah sangat berlangsung lama. Yaitu pada masa Erman Suparno menjadi Menakertrans terbit UU penempatan dan perlindungan TKI yang selama ini dijadikan acuan (No 39/2004). UU itu mengamatkan dibentuknya BNP2TKI sebagai bentuk politik akomodasi pemerintah atas konflik yang terjadi antara lembaga-lembaga pengelola TKI yang pada saat itu di bawah payung APJATI (Asosiasi Pengusaha Jasa TKI) dengan kementerian. Sesuai dengan Perpres No 81 tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI, maka struktur operasional kerjanya berusaha melibatkan banyak unsur: antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain. Dengan harapan, dapat menjembatani berbagai kepentingan itu.
Dalam kenyataannya, kedua insitusi itu hingga kini masih berseteru dalam kepentingannya masing-masing. Bila sudah begini, jangan harap BNP2TKI dapat maksimal bertugas melakukan tugasnya dalam penempatan dan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Sampai pada titik inilah, TKI yang hanya jadi korban, karena tidaknya ada komitmen dan keseriusan dari para pemangku kebijakan dalam menangani mereka.
Jelas, sejak terbentuknya BNP2TKI itu, kondisi perlindungan TKI hingga kini belum juga cukup mengalami perbaikan, sebaliknya malah tambah parah. Tidak ada dalam sejarah penanganan TKI dari tahun 1980 yang begitu buruk justru terjadi setelah dibentuknya BNP2TKI. Meski tidak dapat disebut memiliki hubungan kausalitas, namun faktanya, memang sejak didirikan lembaga yang dalam konstitusinya bertugas melindungi TKI, dalam kenyataannya angka kekerasan yang dialami TKI setiap tahunnya terus meningkat.
Meski tidak terdapat data yang akurat, mengenai angka kekerasan yang dialami para TKI di luar negeri, mengingat pada masing-masing lembaga memberikan data yang berbeda. Kendati begitu, grafiknya memperlihatkan terus menanjak. Dalam hal ini, saya tampilkan di antara data yang dimuat Migrant Care selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 angka kekerasan yang dialami TKI di luar negeri mencapai 1378 kasus. Setahun pasca dibentuk BNP2TKI, angkanya melesat sangat dramatis, yaitu mencapai 1766 kasus pada tahun 2007. Tiga tahun kemudian, angkanya justru melesat, yaitu mencapai 4.532 kasus.
Peningkatan kasus tersebut seiring dengan semakin tingginya jumlah TKI yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke sejumlah negara di luar negeri dalam setiap tahunnya. Menurut kementerian transmigrasi dan tenaga kerja, pada tahun 2009 angka TKI di luar negeri mencapai 25.602 jiwa, meningkat pada tahun 2010 sebanyak 25.833 orang. Masih menurut Migrant Care, total buruh migran Indonesia diperkirakan mencapai 4,5 juta orang.
Berbegai jenis kekerasan yang dialami para TKI kita, mulai dari gaji yang tidak dibayarkan, klaim asuransi tidak dibayar, pelecehan seksual, meninggal penipuan, penelantaran, pengusiran oleh majikan, penyiksaan, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, gagal berangkat, putus komunikasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, hingga sakit yang diabaikan dan pemerasan.
Pada satu sisi BNP2TKI tetap membuka pintu sebesar-besarnya bagi buruh Indonesia ke luar negeri—sehingga terus meningkat dalam setiap tahunnya, namun di sisi yang lain, lembaga ini melakukan pembiaran terhadap munculnya kekerasan yang berulang menimpa para TKI, menunjukkan komitmen perlindungan lembaga ini sangat rendah. Sebaliknya, institusi ini lebih memanfaatkan mereka sebagai lahan bisnis.
Ketika penempatan dan perlindungan TKI masih dilakukan oleh Binapenta dan PPTKLN, keduanya berjalan baik. Akan tetapi setelah BNP2TKI, lebih banyak sibuk mengurusi bagaimana menempatkan TKI agar target perolehan devisa negara setiap tahunnya tercapai. Sementara sisi yang paling penting, yakni perlindungan dan penyelamatan bagi TKI justru malah terabaikan.
Karenanya tidak terlalu berlebihan bila melihat konstruksi UU No 39 Tahun 2004, hampir 93 persen pasalnya membahas soal bisnis penempatan TKI. Adapun yang membahas perlindungan TKI hanya 7 persen pasal saja.
Dalam sebuah catatan Migrant Justice, disebutkan sejumlah praktik permainan yang dilakukan oknum BNP2TKI. Di antaranya keterlibatan oknum BNP2TKI yang menempatkan TKI ke Selandia Baru yang mengarah kepada praktek-praktek Trafficking.
Selain itu, praktik monopoli pada sejumlah pelayanan TKI. Untuk mendapatkan perizinan 1 Quota Kendaraan Angkutan TKI di Terminal 4 Selapanjang, misalnya, PJTKI harus merogoh kocek puluhan juta rupiah, bahkan ada PJTKI yang memiliki 30 Quota Kendaraan.Demikian juga pengusaha yang ingin memiliki izin BNP2TKI membuka tempat usaha di Terminal 4 Selapanjang, harus mengeluarkan biaya ratusan juta. Ironinya, ada oknum-oknum BNP2TKI yang bersedia mengurus keluarnya izin tersebut dari Kepala lembaga tersebut.
Selain juga kasus Committee Korea, bagi personal yang berminat masuk menjadi anggota Committee Korea dikenakan tarif yang tidak sedikit yang juga jumlahnya ratusan juta rupiah/orang.
Ada juga kasus potongan Rp. 10.000/TKI yang sempat berjalan beberapa bulan, Monopoli Tiket pesawat ke Korea & Brunei oleh adik Oknum Kepala BNP2TKI, Penunjukan Perusahaan Medical Check TKI yang harus menyerahkan Rp. 50.000/TKI juga kepada Adik Oknum Kepala BNP2TKI, penunjukan Angkutan DAMRI untuk mengangkut TKI dari terminal 2 ke Terminal 4 Selapanjang dengan biaya Rp. 10.000/TKI sementara ada perusahaan Jasa Angkutan yang menawarkan Rp. 7.000/TKI justru ditolak.
Paling ironis berbagai bentuk pengaduan adanya pemerasan TKI yang pulang melalui Terminal 4 Selapanjang oleh oknum perusahaan Jasa Angkutan TKI, tidak mendapat respon apapun, karena urusan skoorsing bagi angkutan dapat diperjual belikan atau di negosiasikan antara pemilik perusahaan dengan oknum BNP2TKI. Dan banyak lagi praktek-praktek lainnya yang meingindikasikan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan penempatan & perlindungan TKI oleh oknum-oknum di BNP2TKI.
Dua Opsi untuk BNP2TKI
Dengan melihat itu, kita tidak mengharapkan lagi kinerja yang optimal dari BNP2TKI sebagai badan yang bertugas melindungi TKI di luar negeri. Karenanya pilihannya hanya dua untuk lembaga ini, bila tidak dibubarkan, maka ia menjadi salah satu direktorat di Kemenakertrans.
Rasionalisasinya sangat jelas. Pertama, badan ini sudah tidak lagi efektif menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 39 tahun 2004 itu. Kedua, keberadaannya selama ini kerap memposisikan sebagai “lawan tanding” kementerian yang jelas bertentangan dengan cita-cita awal pendiriannya. Ketiga, lembaga ini lebih banyak sibuk mengurusi konflik yang terjadi baik di kalangan internal lembaga itu, atau bahkan dengan kementerian. Kondisi inilah yang membuat tidak lagi produktif keberadaannya. Keempat, semakin banyaknya TKI yang menjadi korban di luar negeri, tanpa penting yang dilakukan oleh BNP2TKI.
Pilihan ini tentu saja akan membawa konsekuensi ekonomi politik yang tidak kecil. Baik bagi para pegawai di BNP2TKI itu sendiri, maupun terkait dengan legitimasi pemerintah. Namun, pihak pemerintah harus berani dan tegas, dibanding harus miris menyaksikan para TKI di luar negeri kita yang setiap tahunnya banyak mengalami kekerasan.
Opsi kedua, bila ingin menghindari krisis legitimasi yang lebih luas dialami oleh pemerintah, maka dapat diambil keputusan dengan memasukan tugas dan peran lembaga itu ke dalam kementerian. Artinya, dibuatkan direktorat tersendiri yang selama ini mengurusi tugas-tugas BNP2TKI. Catatannya, perlu dibuat aturan yang lebih tegas agar terhindar lagi dualisme kepemimpinan atau tumpang tindih peran.
Semua pilihan ini akan sangat tergantung pada posisi politik pemerintah. Namun kita berharap, kemana pun arahnya atau kebijakannya, yang paling utama dan terutama adalah kepentingan perlindungan bagi para TKI.